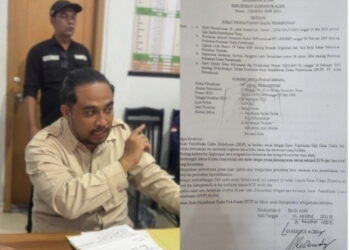Oleh: Alja Yusnadi
Apa yang Anda bayangkan jika mendengar Pancasila? Narasi ini seperti penting-tidak penting untuk ditanya. Dulu, semasa saya Sekolah Dasar, Pancasila itu untuk dihafal, dinyanyikan. Yang oleh karenanya bisa cepat pulang sekolah, yang karenanya pula bisa berdiri sebelah kaki di depan kelas.
Itu adalah Pancasila yang saya pahami sekitar 25 tahun yang lalu, Pancasila bagi anak-anak. Saya senang saja menghafalnya, yang setiap hari senin pula selalu diulang-ulang di upacara bendera. Saya juga pernah mengikuti lomba cerdas cermat yang bertema Pancasila.
Memasuki Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pancasila dikembangkan lebih luas. Sebelum memulai proses belajar-mengajar, terlebih dahulu pengikuti penataran P4. Kalau saya tidak salah, P4 itu singkatan dari: Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Bayangkan, bagaimana posisi Pancasila pada saat itu, dipedomani, dihayati, lalu—entah iya–diamalkan. Saya lupa isinya, selanjutnya Pancasila dibicarakan di pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Begitulah. Pancasila yang “ditemukan” di orde lama, dikembangkan oleh orde baru. Berikutnya, saya mulai mempertentangkan Pancasila. Ada dua sebab, Pertama, akibat hegemoni perlawanan Aceh terhadap pemerintah pusat. Kedua, sebagai akibat dari hegemoni yang dikembangkan oleh kelompok tertentu yang menyebut Pancasila sebagai berhala.
Tidak bisa dipungkiri, di masa perlawan bersenjata, apa saja yang berbau Pemerintah Pusat salah, dan harus dimusuhi. Saya tidak tahu kenapa pula Pancasila ikut-ikutan dimusuhi, padahal dia adalah nilai-nilai, bukan pemerintah, tidak pula bersenjata.
Kemudian, saya mendengar beberapa pemikiran—entah layak disebut pemikiran atau cuma jargon—bahwa Pancasila itu adalah berhala, dan oleh karena itu pula tidak boleh dibangga-banggakan. Ya, yang namanya juga anak muda, berdarah panas, asal beda, apalagi beda dengan mayoritas, sudah menjadi kebanggaan.
Itu yang paling kanan, di saat saya bersentuhan dengan yang paling kiri, juga mengenyampingkan—minimal, tidak pernah membahas– yang lima sila itu. Menurut pendapat itu, yang paling utama adalah menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat.
Benarkah demikian? Seperti saya uraikan tadi, saya sudah mulai mendengar dan menghafal Pancasila 25 tahun yang lalu. Namun, saya mulai mempelajari dan menghayatinya beberapa tahun setelah dewasa. Saya belum menemukan esensinya mulai dari sekolah rendah, sampai sekolah tinggi.
Saya “menemukan” pentingnya Pancasila setelah membaca beberapa pidato Bung Karno, Negara Paripurna nya Yudi Latief, biografi Bung Karno yang ditulis Cindy Adam, Bung Karno Islam dan Pancasila nya Ahmad Basarah, Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam nya Hamka Haq.
Memang belum lengkap, saya harus membaca sejarah Pancasila itu dari sudut pandang Hatta, Yamin, dan lainnya.
Bukan untuk diratapi, tapi harus kita akui, di masa orde baru, terjadi Desoekarnoisasi. Sebuah upaya untuk menghilangkan nama Soekarno secara sistematis, termasuk perannya dalam menggagas Pancsila.
Politik-kekuasaan mengharuskan Soeharto–yang membangun pondasi di atas bangunan yang sudah didirikan Soerkarno–untuk mengurangi pengaruh Soekarno bahkan menghilangkannya samasekali.
Setelah reformasi, Pancasila perlahan dikembalikan sebagaimana gagasan awal dengan berbagai konsekuensinya.
Pancasila itu lahir dari penyatuan sikap politik, penyatuan cara pandang dalam melihat Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup turun-temurun. Itulah yang menajdi dasar Indonesia Merdeka.
Bangunan besar itu harus memiliki pondasi yang kokoh, itulah peran Pancasila bagi Indonesia yang raya ini. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang Berkebudayaan menjadi preamble konstitusi Indonesia.
Pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar harus menjabarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
Kita bisa membayangkan bagaimana suasana kebatinan para pendiri bangsa pada saat itu. Satu sisi harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang terus dibayang-bayangi Jepang, di sisi lain harus berjibaku dengan teman sendiri untuk merumuskan dasar Indonesia Merdeka.
Benturan antara tokoh kebangsaan dengan tokoh agama sudah nampak pada saat itu. Bagi tokoh seperti Abi Kusno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H Wahid Hasyim, Agoes Salim, dasar Indonesia haruslah berlandaskan Islam.
Pertautan antara pemikiran tokoh Islam dan tokoh Kebangsaan itu tercermin dari redaksi pembukaan UUD: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..”
Selanjutnya, dipindahkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ke sila pertama merupakan perwujudan dari menghormati pemikiran tokoh agama.
Pada sisi lain, pada sidang PPKI tokoh agama “merelakan” tujuh kata pada sila pertama itu untuk dihapus.
Perdebatan itu bukan tidak sengit. Tapi pada akhirnya masing-masing pihak dapat memahaminya. Para pendiri bangsa ini telah sepakat memilih Pancasila sebagai sebuah Konsensus nasional.
Indonesia sudah mencoba beberapa model demokrasi. Mulai demokrasi terpimpinnya Soekarno, demokrasi ordebarunya Soeharto, demokrasi pasca reformasi. Kesemua model demokrasi itu masih menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai.
Belakangan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, masih saja ada pihak-pihak yang ingin menukar Pancasila. Padahal kita sudah melihat, bagaimana di belahan dunia lain, suatu negara yang terdiri dari sedikit suku, etnis, ras, saling gontok-gontokan, tidak memiliki dasar negara yang kuat.
Di situlah pentingnya Pancasila sebagai landasan kita bernegara. Walaupun, di tengah hegemoni teknologi seperti sekarang ini, negara harus mencari cara, agar Pancasila itu bisa hidup, dihayati dan diamalkan oleh generasi Z.
Akhirnya, kita harus berterima kasih kepada para anggota BPUPK, anggota PPKI yang telah bersusah payah menyepakati konsensus ini, terutama Bung karno yang telah memperkenalkan Pancasila sebagai landasan Indonesia Merdeka.
Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945-1 Juni 2021.