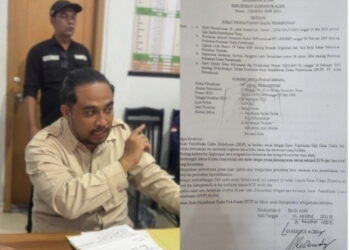Oleh: Alja Yusnadi
Tulisan ini tidak bermaksud mencari benang merah tentang pewaris Aceh secara legal-formal. Aceh telah menjadi provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang diatur melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Memperdebatkan sejarah Aceh tentu tidak bisa melalui tulisan yang panjangnya hanya 700-1000 kata. Menyurah di pos jaga ditemani kacang rebus dan kopi pahit tidak akan habis dalam masa satu bulan suntuk.
Sebegitulah panjang sejarah Negeri bertuah itu. Saya bukan ahli sejarah atau orang yang pernah melakukan penelitian di bidang sejarah. Bukan, bukan samasekali. Kalaupun ada nanti informasi sepotong dua potong tentang Aceh yang saya tulis, itulah hasil dari membaca beberapa karya ahli sejarah. Kalau dipaksa tanya, pendidikan formal ihwal sejarah ini hanya saya dapatkan di sekolah, itupun saya tidak ingat lagi.
Hasrat menulis tentang Aceh ini didorong oleh beberapa kejadian dalam tempo satu bulan ke belakang. Pertama, sejumlah orang yang mengaku sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan unjuk rasa di halaman Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. Bertepatan dengan peringatan 15 tahun Damai Aceh, 15 Agustus 2020. Pengunjuk rasa mendesak Wali Nanggroe agar menaikkan bendera Aceh yang telah disahkan oleh DPR Aceh—Pemerintah Pusat belum menyetujuinya.
Kedua, Plt. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) melantik keluarga besar bangsawan Aceh. Ketiga, Majelis Istiadat Diradja Kerajaan Aceh Darussalam melaksanakan pengibaran bendera Alam Peudeung dalam rangka memperingati tahun baru Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah di Istana Darul Ihsan, Banda Aceh.
Ketiga peristiwa itulah yang membuat hasrat saya menggebu untuk mengontruksikannya, minimal sependek selera saya. Nampaknya mereka tidak saling terkait. Karena tidak saling mengurusi urusan yang lain.
Masing-masing kelompok yang mewakili sejarahnya tampil merefresentasikan Aceh masa lampau, masa kini dan masa depan. Aceh memang memiliki sejarah yang panjang, berliku seperti Krueng Daroy.
Secara singkat, sejarah Aceh saya kelompokkan menjadi tiga fase: Kerajaan, Pasca Kerajaan, dan Aceh 1976. Pengelompokan ini untuk memudahkan pengidentifikasian.
Pada masa Kerajaan, kedaulatan dan kedudukannya jelas. Bagaimana gegap gempitanya sampai ke Turki, hubungan diplomatik sampai ke Kerajaan Inggris.
Kejayaan itu hampir tidak meninggalkan bekas, sebagaimana Kesultanan Yogyakarta yang bangunan dan Sultannya masih eksis sampai sekarang. Kabarnya, banyak situs sejarah yang dihilangkan oleh Belanda.
Diakhir cerita itulah sejarah mulai bercabang, banyak macamnya. Selain Sultan, Aceh juga memiliki Ulee Balang dan Ulama. Kedua kelompok tersebut ikut bersentuhan dengan Belanda. Ada yang melawan, ada pula yang berkawan.
Entah dimulai darimana, sampai sekarang ada yang mengklaim keturunan dari Kesultanan Aceh. Ada pula sebagai pemangku Wali Kesultanan.
Anthony Reid menyebutkan dalam bukunya Asal Mula Konflik Aceh, pada akhir 1880-an, Teungku Tiro dari kalangan Ulama mendapat legitimasi dari Sultan melalui Cap Sikureung—Stempel Kesultanan—sebagai pemimpin agama tertinggi.
Walaupun hanya penegasan atas apa yang sudah diraihnya, setidaknya Cap Sikureung itu menghindari iri-dengki dari kaum Ulee Balang karena berkurangnya pengaruh mereka. Dari sini sudah terlihat ada gesekan.
Kemudian, sejarah Aceh terakhir dimulai pada tahun 1976. Bersamaan dengan dideklarasikannya Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro—Sosok ini yang pada saat Aceh damai menjadi Wali Naggroe pertama–. Aceh pada masa itu telah di menjadi Provinsi.
Perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia terjadi pada Agustus 2005, atau 29 tahun setelah Hasan Tiro memproklamirkan kemerdekaan. Dan, kelanjutan dari sejarah terakhir inilah Lembaga Wali Nanggroe di legalkan, diakui secara yuridis. Persoalan tugas pokok, nanti kapan-kapan kita bicarakan dalam kesempatan lain yang lebih panjang.
Saya perhatikan, masing-masing tahapan ini memiliki kelompok sepesialis tersendiri. Tidak melibatkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat Aceh. Hal ini pula yang mengakibatkan tersendatnya beberapa agenda pasca damai.
Lihatlah, dalam waktu hampir bersamaan ada tiga kelompok spesialis sejarah yang menggelar acara, semua berdasarkan imajinasi masing-masing. Semua pula bergerak sendiri-sendiri. Kelompok Bendera Bintang Buleun mendesak agar pemerintah memberikan izin bendera Aceh itu naik.
Lain pula dengan kelompok Alam Peudeung, mereka tidak memerlukan qanun atau legalisasi apapun, namun hampir setiap tahun melakukan upacara peringatan tahun baru Islam dengan meggerek Alam Peudeung ke angkasa bersama dengan bendera Merah Putih.
Kelompok ini juga melakukan hubungan “bilateral” dengan Kerajaan-Kerjaan yang masih eksis di luar negeri, sebut saja misalnya Kerajaan Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam dan berbagai Kerajaan lain. Mereka aktif menghadiri acara-acara Kerajaan.
Tidak mau kalah, mereka yang mengaku sebagai kaum bangsawan juga menampakkan eksistensi. Mereka justru menggandeng MAA. Saya kurang tahu dari garis mana keturunan bangsawan ini menarik sumbu.
Belum lagi kita turun ke bawah, ke daerah-daerah, seperti Meureuhom Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, ada beberapa yang mengaku sebagai keturunan Kerajaan setempat. Mereka menggelar beberapa upacara adat.
Akhirnya, masing-masing berjalan dengan agenda sendiri, bermimpi masing-masing, walaupun tidur satu ranjang, tinggal satu rumah. Tidak ada yang salah dari kegiatan itu. Lagi pula, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Kita anggap saja kegiatan tersebut untuk menghargai sejarah.
Akan tetapi, mau bagaimanapun ditarik Aceh itu, yang namanya Aceh tetaplah Aceh. Aceh yang majemuk, Kosmopolit, Aceh yang menemukan jalannya sendiri. Kelompok-kelompok itu tadi menjadi bagian tak terpisahkan dari negeri bertuah yang bernama Aceh.
Negeri yang penghuninya tidak mau takluk begitu saja kepada Belanda, namun tak selalu patuh kepada perintah Sultan. Saking repotnya mengurus Aceh, Belanda mengirim antropolog untuk meneliti titik lemah orang Aceh: C. Snouck Hurgronje.
Masing-masing menerima warisan sesuai porsi. Namun ada kendala sedikit ihwal waris-mewariskan itu, kalau genetik bisalah diturunkan, semisal bangsawan. Bisa jadi, dalam tata kelola Pemerintah pada saat itu, para bangsawan memiliki kontribusi dan pengaruh khusus terhadap Kerajaan. Nah, kalau sekarang? Berbeda samasekali. Jadilah gelar itu diwarisi tanpa konsekwensi apa-apa.
Berbeda dengan ulama, pewarisnya bukan secara genetika. Pewarisnya adalah murid yang belajar hingga tuntas.
Mengakhiri tulisan ini, biarlah semuanya mewarisi apa yang berhak mereka warisi. Tidak usahlah mewarisi Aceh secara keseluruhan. Bukan apa-apa, orang-orang seperti saya ini yang bukan bangsawan, bukan ulama, bukan GAM mewarisi Aceh menurut yang saya punya. Kecuali, sesuatu yang diwariskan langsung oleh Yang Maha Kuasa melalui Kekasih-Nya.
Tulisan ini sudah pernah tayang di Kumparan