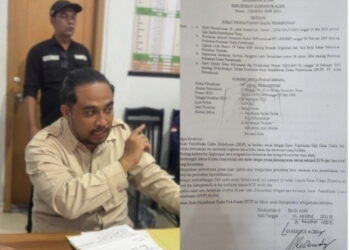Oleh: Alja Yusnadi
Dini hari di pertengahan Oktober, sambil menikmati Boh Manok Weng–Telur ayam kocok–saya berdiskusi ringan dengan beberapa orang kawan.
Mulanya, diskusi itu secara tidak berurutan menyinggung berbagai aspek: sosial, politik, kebijakan publik, dan sesekali menyerempet ke persoalan domestik.
Terakhir, tema diskusi fokus mengenai Pancasila, Nasionalisme, dan Indonesia. Ini bukan seminar, jadi pembahasannya tidak beraturan.
Sampailah pada pertanyaan, “Apakah pada saat itu, basis perlawanan rakyat terhadap kolonial adalah Indonesia? atau kesadaran masing-masing daerah untuk tidak mau tunduk kepada penjajah?” Tanya seorang kawan.
Tentu banyak sekali jawabannya. Tergantung kurun waktu, tergantung siapa yang menjawab, dan melihat dari perspektif mana.
Sebelum tahun 1945, bisa jadi perlawanan-perlawanan rakyat di daerah tidak dalam satu komando. Masing-masing begerak sendiri. Teuku Umar di Aceh tidak ada komunikasi dengan Ngurah Rai di Bali atau dengan pahlawan yang sezaman dengannya.
Pada saat itu belum ada media sosial, teknologi masih sangat terbatas. Tidak ada group WA, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada Istagram. Konsolidasi nasional agak terhambat.
Setelah Indonesia merdeka, perjuangan itu sudah menjadi milik semua kalangan. Mulai dari Tentara, pemuda, hingga santri.
Perjalanan panjang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi santri, pesantren, dan Nahdatul Ulama (NU). Tentu, dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lainnya.
Karena perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah pekerjaan bersama: gotong royong.
Kontribusi ulama dan santri itu bisa kita lihat mulai dari perumusan dasar negara–sidang BPUPK– yang melibatkan tokoh NU seperti KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Abdul Fatah Yasin, sampai mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan Indonesia.
Sebelum Indonesia merdeka, NU sudah berdiri, 31 Januari 1926. Jadi, bisa dipahami, bagaimana gigihnya NU dalam mempertahankan Indonesia.
NU menjadi induk organisasi, tempat berkumpulnya para ulama. Pesantren merupakan tempat para ulama itu mengabdi, mendidik anak bangsa, menjadi tempat menempa generasi muda.
Santri adalah para anak bangsa itu, yang hidup dan berkembang di pesantren di bawah asuhan ulama.
Para santri sangat takzim kepada ulama, terutama yang menjadi gurunya. Relasi ini lebih dari sekedar guru dan murid. Melebihi prajurit dengan komandan. Loyalitas tanpa batas.
Karena hubungan erat itulah, ulama memiliki peran sentral dalam menggerakkan santri dan masyarakat untuk melawan penjajah.
Setidaknya, saya mencatat dua peristiwa penting yang sangat mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia dan itu adalah kontribusi ulama dan santri.
Pertama, di saat panitia 9 merumuskan dasar negara. Awalnya sudah tercapai kesepakatan, sila pertama; Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya.
Ide itu muncul—setidaknya ikut mengusulkan—dari Wahid Hasyim. Belakangan, salah satu anggota yang berasal dari Indonesia Timur memprotes penggunaan 7 kata setelah Ketuhanan.
Akhirnya, Wahid Hasyim dapat menerima dan mengganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap Wahid itu penuh penghayatan, jika didorong voting, kemungkinan besar opsi pertama akan menang. Betapa luhurnya pemikiran para tokoh bangsa saat itu.
Kedua, di saat Belanda dan sekutu ingin kembali menguasai Indonesia, beberapa bulan setelah Indonesia merdeka.
Hal ini membuat NU marah. KH. Hasyim Asyari yang saat itu menjabat sebagai Rais Akbar PBNU mengeluarkan resolusi jihad. Menurut Hasyim, ulama dan santri wajib berjuang mempertahankan Indonesia.
Resolusi itu dikeluarkan Hasyim pada 22 Oktober 1945. Para ulama dan santri merespon dengan maju ke medan tempur. 21 dan 22 Oktober digelar pertemuan di Surabaya.
Ulama, santri, pemuda dan masa rakyat bersatu, melawan penjajah. Peristiwa ini memicu pertempuran luar biasa yang pada akhirnya menewaskan Jendral Aulbertin Walter Sothern Mallaby.
Begitulah, bagaimana peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Dapat saya pahami, kenapa NU dalam perjalanan bangsa Indonesia selalu mengambil sikap untuk menjaga keutuhan dan selalu bergandengan tangan dengan kaum nasionalis.
Upaya mempertahankan keutuhan dalam keberagaman ini kadang-kadang mendapat perlawanan dari kelompok Islam lainnya. Lihat saja bagaimana seorang anggota Banser—sayap NU—mengorbankan jiwanya untuk menjaga malam natal.
Ceramah-ceramah Kiyai NU juga sangat bernuansa Indonesia, jarang menghasut untuk mempertajam perbedaan.
Akhir-akhir ini, makin marak saja kelompok Islam yang berbeda cara pandang dengan NU dalam melihat Indonesia dan Islam.
Pada tahapan ini, kita yang masih menginginkan Indonesia ada harus berterimakasih kepada NU dan santri. Jika ada 10 organisai yang ingin Indonesia utuh, NU salah satunya, jika ada 5, NU salah satunya, jika ada 3, NU salah satunya, jika tingal 1, itulah Nahdhatul Ulama.
Pun demikian dengan Pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Untuk mengenang kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia.
Itu belum cukup. Pemerintah harus menjadikan pesantren, sebagai salah satu institusi pendidikan yang diakui keberadaannya.
Suatu saat, alumni pesantren—santri—bisa mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi polisi, tentara, pegawai pemerintah. Sama seperti kesempatan yang dimiliki oleh alumni institusi pendidikan lainnya.
Tentu tidak bisa instan dan tergesa-gesa. Pemerintah harus merumuskan dengan seksama dengan melibatkan ulama dan pesantren.
Menjawab pertanyaan kawan saya tadi, Indonesia ini turut diperjuangkan oleh ulama dan santri. Mungkin karena alasan itu pula, Pancasila sudah 75 tahun merajut Nusantara.
Bagaimanapun Komunis dan Khilafah mencoba mengubah haluan negara, ternyata solusi terbaik masih Pancasila. Persoalan kesejahteraan, dan lain-lain, itu harus diselesaikan dengan seksama oleh penyelenggara negara dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Walau telat sehari, untuk para santri, aneuk dayah, termasuk santri pesantren kilat, Selamat Hari Santri, Ya…[Alja Yusnadi]