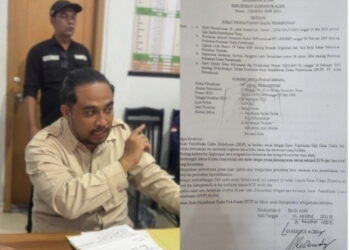Oleh: Alja Yusnadi
Manusia, di awal kehadirannya hidup berpindah-pindah, sangat tergantung pada alam, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Lalu, kehidupan itu berkembang. Berkelompok-kelompok, berkapilah-kapilah. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup juga berkembang. Mulai ditemukan teknologi bercocok tanam.
Sejalan dengan perjalanan waktu, manusia terus berevolusi yang kalau mengutip Yuval Noah Harari menyebutnya Homo Sapien. Pola pemenuhan kebutuhan manusia juga sudah mulai beragam.
Semakin ke sini, penduduk bumi semakin banyak, teknologi terus berkembang, kebutuhan yang harus dipenuhi juga terus bervariasi.
Kehidupan berkelompok terus berevolusi menjadi berbagai bentuk. Kelompok-kelompok itu semaki besar dan beragam coraknya. Ada yang berbentuk Kerajaan, Republik, dan berbagai nama lain.
Perkembangan tersebut juga berbanding lurus dengan beragam gesekan sosial-politik yang ada di masyarakat.
Gesekan itu bisa saja terjadi antar negara, beberapa negara bersekutu bentrok dengan negara lain yang bersekutu pula. Ada gesekan yang terjadi di dalam negara, sesama satu negara. Ingin berpisah dari negara induknya.
Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, Indonesia beberapa kali terjadi pergolakan di dalam. Aceh, Papua, Timur Leste adalah yang eskalasinya paling tinggi. Bahkan, Timur Leste sudah berhasil memisahkan diri dan menjadi negara sendiri.
Dua nama lain sudah mendapatkan otonomi khusus yang tidak dimiliki daerah lain, kecuali Yogyakarta karena sejarahnya, DKI Jakarta karena Ibukotanya.
Kali ini, saya ingin menulis tentang gesekan yang terjadi di Aceh. Diakui atau tidak, sejarah panjang telah menempatkan Aceh sebagai entitas yang paling tidak bisa diam ketika ada gejolak sosial.
Kita Tarik saja garisnya setelah Indonesia merdeka. Ada dua perlawanan besar yang digerakkan oleh sebagian tokoh Aceh yang mau tidak mau merepotkan Pemerintah pusat.
Pergolakan pertama melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini dikomandoi oleh Daud Beureueh. DI/TII Aceh berafiliasi dengan DI/TII di daerah lain, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan beberapa daerah lain.
Salah satu yang mempertemukan kepentingan antar daerah ini adalah mengkoreksi relasi pusat dengan daerah. Daud Beureuh meminta Aceh untuk menjalankan syariat islam dan kembali menjadi provinsi sendiri.
20 September 1953, Daud Beureuh mendeklarasikan Aceh bergabung bersama Negara Islam Indonesia.
Setelah beberapa tahun bergeriliya, DI/TII Aceh terbelah. Pada 8 April 1957, di bawah komando Hasan Saleh, DI/TII memilih jalan dialog dengan Pemerintah.
Mengutip Murizal Hamzah dalam bukunya Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Perundingan marathon ini yang kemudian dikenal dengan Ikrar lamteh—karena diadakan di rumah salah seorang anggota DI/TII yang terletak di daerah Lam Teh– ini berhasil menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan menjalankan keistimewaan di bidang agama, pendidikan, adat-istiadat.
Selain itu, perjanjian ini juga mengatur tentang: Indonesia memberikan ganti rugi akibat perang DI/TII, memberikan amnesti kepada anggota DI/TII, mengangkat tentara DI/TII sebagai perajurit TNI.
Pemerintah Indonesia juga memberi fasilitas tertentu kepada elit DI/TII, memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh.
Walaupun Hasan Saleh dan beberapa pentolah DI/TII telah berdialog dengan Pemerintah, Daud Beureuh masih tetap memimpin geriliya di pedalaman Aceh.
Secara spordis, pasukan Daud Beureueh terus melakukan penyerangan kepada tentara Indonesia.
Akhirnya, pada 9 Mei 1962, Daud Beureuh bersedia turun gunung bersama pengikut setianya. Sebagai tindak lanjut, Pangdam Iskandar Muda mengadakan Musjawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).
Pertemuan ini menghasilkan Ikrar Blang Padang (22 Desember 1962) yang salah satu keputusannya mengubah nama Lapangan Gajah—Semasa Kolonial Belanda namanya Wilhelmina Esplande– menjadi Blang Padang.
14 tahun berikutnya, Hasan Tiro kembali mendeklarasikan Aceh Merdeka. Gerakan ini juga sama, hendak memisahkan Aceh dari Indonesia.
Walapun terjadi pergeseran sedikit bentuk perjuangan, namun Hasan Tiro tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pergerakan yang pernah dibangun oleh Daud Beureueh.
Secara tidak langsung, Hasan Tiro muda sudah terlibat, minimal sekali secara pemikiran terhadap pergerakan yang dibangun Daud Beureueh.
Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro menyatakan Aceh Merdeka. Bersama pasukannya, Hasan Tiro ingin memerdekakan Aceh.
Setelah keluar-masuk hutan untuk bergeriliya, akhirnya Hasan Tiro memimpin perlawanan dari luar negeri.
Beberapa gelombang anak muda Aceh dikiirim ke Libya untuk mendapatkan pendidikan militer.
Di Aceh, pasukan Aceh Merdeka terus bergerak, merekrut tokoh dan masyarakat untuk bergabung dalam barisan Aceh Merdeka.
Perjuangan itu pasang surut. Apalagi, sejak tahun 1989, Pemerintah menerapkan Daerah Operasi Militer di Aceh. Misinya untuk menumpas Aceh Merdeka.
Ini adalah operasi tersadis yang pernah ada. Banyak sekali peristiwa yang merendahkan kemanuiaan terjadi di Aceh. Sampai akhirnya di cabut pada tahun 1998 beriringan dengan meledak-meletupnya politik Indoneisa menjelang reformasi.
Sepertinya, kekisruhan di Jakarta berdampak positif terhadap perjuangan Aceh Merdeka. Animo masyarakat untuk bergabung semakin tinggi. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pasukan TNI semakin kencang. Eskalasinya semakin tinggi.
Beberapa perjanjian damai gagal menghentikan permusuhan secara permanen: Jeda Kemanusiaan (12 Mei 200), Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) yang berlangsung pada 9 Desember 2002.
Hingga akhirnya Memorandum of Understanding (moU) Helsinki pada tahun 2005. Sejak itulah, konflik bersenjata itu dapat dihentikan, ditambah lagi karena terjadi Tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004.
Begitulah, beberapa perjanjian ikut mewarnai sejarah Aceh. Tentu, setiap perjuangan itu memiliki imajinasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Baik secara ekonomi, baik secara politik, dan berbagai kebaikan lainnya.
Tulisan ini sudah pernah tayang di Kolom: AY Corner anteroaceh.com