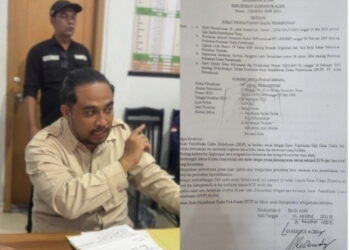Oleh: Alja Yusnadi
Perayaan adalah wujud rasa syukur. Melampiaskan kegembiraan. Berterimakasih kepada alam dan pemilik-Nya, atas apa yang telah dicapai.
Ada berbagai hal yang sering dirayakan. Dalam skala tertentu kita merayakan berbagai peristiwa penting di dalam hidup. Misalnya, sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, setiap 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan.
Ekpresinya macam-macam, mulai dari panjat pinang—hiburan rakyat—sampai menggelar upacara bersama diberbagai tingkatan.
Penganut agama Islam, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW—ada juga yang tidak—, Idul Fitri, Idul Adha, dan berbagai perayaan lain. Begitu juga dengan penganut agama lain, memiliki hari besar yang dirayakan setiap tahunnya.
Turun sedikit, cakupan yang lebih sempit, suami istri merayakan hari ulang tahun perkawinan, merayakan hari lahir. Dan seterusnya.
Bagaimana dengan perayaan setiap 30 September? Ini perayaan model lain. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang saya sebut di atas.
Saya sebut perayaan, karena dalam rentang waktu 1984-1998 negara memutar film yang diberi nama G 30 S PKI—Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
Seterusnya, pasca 1998, setiap bulan September kita disibukkan dengan isu kebangkitan PKI berikut turunannya.
Apa yang hendak dirayakan pada tanggal tersebut? Kehancuran PKI? Cikal bakal Orde Baru? Atau gesekan Angkatan Darat?
Ketiganya mendapat porsi tersendiri. PKI hancur, berkeping pasca peristiwa itu. Lima bulan setelahnya, Soeharto mendapat perintah untuk mengurus Indonesia melalui Supersemar—yang sampai saat ini masih diperdebatkan—dan menjadi cikal-bakal Orde Baru selama 32 tahun menguasai Indonesia.
Keterlibatan Angkatan Darat juga tidak dapat disangkal, karena pelaku dan korbannya –yang disajikan dalam film itu–sama-sama Angkatan Darat. Hanya saja, pelakunya disebutkan menjadi bagian dari PKI.
Sebenarnya, apa yang kita rayakan setiap 30 September itu?
Jawabannya beragam. Tergantung kita berdiri di sudut mana. Ada yang merayakan keruntuhan PKI, ada yang merayakan awal berkuasa. Mungkin juga perayaan dengan perasaan yang berbeda.
Seperti Idul Fitri, anak-anak merayakan dengan baju dan mainan yang serba baru. Orang “dewasa” memaknai sebagai “awal hidup baru”.
Negara, agama, boleh saja memfasilitasi perayaan itu, namun tidak bisa memaksakan hikmahnya.
Di Indonesia, PKI telah lama mati, tersungkur, terkubur, berikut pemikirannya. Pun di Soviet dan Eropa sana, tempat lahirnya para pencetus gagasan Komunis itu.
Yang tersisa, beberapa negara di Amerika latin juga jalan terseok. Negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, seperti kehendak awalnya.
Keberhasilan Komunis—itupun sudah dimodifikasi—hanya dapat dilihat dari China, mungkin ditambah Vietnam dan Kamboja. Kalau tidak di embargo, barangkali juga Korea Utara.
Beberapa negara yang saya sebut terakhir itu memang sedang merangkak, naik, bersaing dengan Amerika untuk menjadi raksasa dunia. Pun termasuk negara yang paling berhasil dalam menangani Korona.
Lalu, apa yang ingin kita rayakan di penghujung September itu?
30 September adalah salah satu noktah sejarah bangsa kita.
Kita perlu mengenang sejarah kelam itu, agar terhindar di masa depan. Sebagaimana negara-negara lain mengenang sejarah kelam bangsanya.
Tidak mudah meluruskan sejarah itu, namun yang paling mungkin adalah memberikan ruang kepada setiap orang untuk mengisi ruang sejarah itu, walau berbeda-beda. Lalu, menarik kesimpulannya, masing-masing.
Generasi ketiga dari keluarga—baik keluarga pahlawan revolusi maupun keluarga PKI—sudah menuju rekonsiliasi.
Bagi yang merayakan dengan cara menonton film karya Arifin C Nor itu, silahkan. Putar semalam suntuk tidak jadi masalah. Bagi yang merayakan dengan membaca berbagai referensi itupun tidak masalah. Ruang bagi yang tidak merayakanpun disediakan.
Yang jangan, merayakan untuk kepentingan politik. PKI dijadikan tangga untuk menggapai mahligai kekuasaan. Karena itu lebih kejam dari PKI itu sendiri, karena berdiri diatas ribuan, ratusan, bahkan jutaan korban yang disebabkan oleh sejarah kelam itu…[Alja Yusnadi]