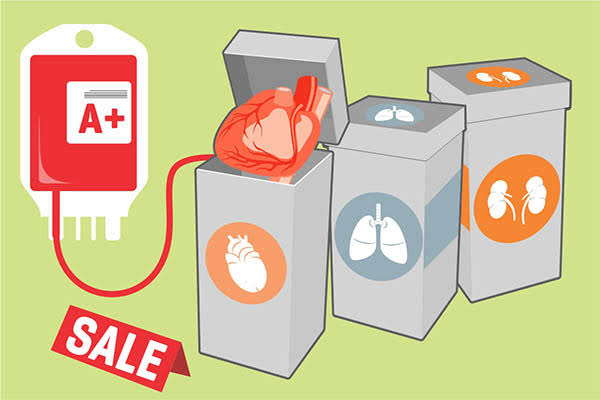Oleh: Alja Yusnadi
Menulis tentang seseorang yang tidak pernah kita jumpai secara fisik bukan perkara mudah. Itulah yang saya rasakan ketika hendak menulis—sedikit saja—tentang mendiang Mahbub Djunaidi, si kolumnis bukan alang-kepalang itu.
Akan tetapi, sebagai Mahbubian—jika tidak berlebihan—atau penulis pemula yang menyenangi gaya Mahbub menulis, kesukaran itu harus dilawan.
Bukan apa-apa, hari ini, tepat 25 tahun kepergian Mahbub. Jadi bolehlah kita mengingat seraya mengirim doa ala kadarnya untuk seseorang yang tulisannya terus kita baca.
Mengenang Mahbub, tidak terlepas dari tiga hal pokok: Wartawan, Kolumnis, Politisi. Ketiga “profesi” itu menemani keseharian Mahbub.
Kebetulan pula, saya juga menyenangi dan pernah melakoni—dalam taraf berbeda—ketiga “profesi “itu.
Bagi wartawan, apalagi yang bernaung di bawah bendera Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tidak boleh tidak harus mengenal sosok Mahbub. Pada saat itu, PWI satu-satunya organisasi profesi wartawan, dan Mahbub pernah menjadi Ketuanya.
Mahbub menjadi Ketua Umum PWI melalui Kongres XII, dua bulan setelah meletusnya peristiwa 30 September 1965. Jakob Oetama—pendiri Kompas– mendampingi Mahbub sebagai Sekjend.
Sebagai Kolumnis, Mahbub terhitung penulis ulung di masanya. Dia pengasuh tetap rubrik Asal-usul—yang kemudian menjadi judul buku kumpulan kolom Mahbub– di Harian Kompas. Mahbub juga menulis Kolom di Tempo dan beberapa Media lainnya.
Mahbub, dalam tulisan-tulisannya tergolong “generalis”. Dia menulis apa saja yang menurutnya penting untuk ditulis. Tidak terbatas pada isu tertentu saja. Mahbub, dengan mengalir bisa menuis perihal politik, internasional, agama, sejarah, dan berbagai topik lainnya.
Itu, bukan pula menujukkan matinya kepakaran seperti yang dimaksud Tom Nichols. Sebagai penulis kolom—menurut saya—tidak perlu pakar dalam pengertian akademik, kecuali ingin menulis jurnal yang terindeks scopus.
Cirikhas tulisan Mahbub dibumbui humor-humor kecil, satire, lucu. Hal ini, menurut saya dipengaruhi oleh kegemaran mahbub membaca sastra Rusia. Tulisan mahbub penuh siasat, sekali-dua kali pukul tidak terasa. Padahal, melalui tulisannya, Mahbub sedang menusuk, mengkritik. Di sinilah kekuatan tulisan Mahbub, selain bahasanya yang membumi, dipahami semua kalangan.
Laki-laki yang suka dipanggil Bung itu, dalam menulis juga tidak melihat sandal kaki atau warna rambut. Bukan berarti kalau kawan luput dari tulisannya yang dikenal tajam dan kritis.
Muhamamd Isnaini yang sudah merasakan. Mahbub mengkritik Isnaini—Wakil Ketua DPR dari PDI—karena jabatannya. Padahal, Isnaini juga berangkat dari latar belakang wartawan, sama seperti Mahbub.
Sebagai politisi, Mahbub juga mencapai puncak kejayaan, pernah menjadi anggota DPR RI dan masuk dalam jajaran pengurus DPP PPP.
Dalam rentang waktu tertentu, orang-orang seperti Mahbub hadir sebagai pemecah kebuntuan. “Kiyai” NU ini hadir ditengah kuatnya hegemoni Orde Baru. Pertama sekali Mahbub mengurus media sekitar 1960. Saat itu, Mahbub menjadi Pimpinan Redaksi Duta Masyarakat, medianya NU hingga 10 tahun kemudian.
Mahbub telah menorehkan sejarah. Dirinya diingat oleh banyak orang. Sampai-sampai PMII—organisasi mahasiswa yang dia dirikan—menggelar Haul Mahbub.
Menjelang subuh, 1 Oktober 1995, Mahbub meninggal dunia. Jasadnya boleh saja terkubur, namun karya-karyanya masih tetap hidup mengisi ruang literasi. Alfatihah…[Alja Yusnadi]