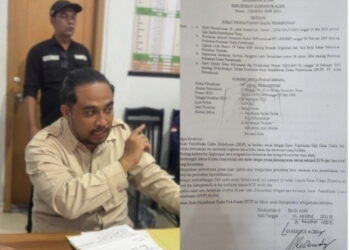Oleh: Alja Yusnadi
Bandul kebijakan pemerintah tentang desa—dalam Bahasa Aceh disebut gampong– terus bergerak menuju formasi terbaiknya. Terakhir, melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 pemerintah mengatur tentang desa.
Sejak tahun 2015, gampong, melalui dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dapat membayar gaji kepala desa (Geuchik) beserta perangkat, melakukan pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rata-rata gampong sudah mengelola anggaran satu milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran periode sebelumnya, ini tentu angka yang sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan apa yang telah diberikan gampong: sumberdaya alam, sumberdaya manusia, angka tersebut belum ada apa-apanya.
Agar efektif, pengelolaan sumberdaya keuangan itu harus berjalan maksimal. Harus memberi dampak kepada perekonomian masyarakat.
Masyarakat gampong harus ikut berpartisipasi dalam rapat-rapat pengusulan program dan ikut mengawasi pelaksanaannya.
Penggunaan dana gampong itu, selain untuk menggaji aparatur, membangun insfrastruktur, yang tidak kalah penting adalah membangun perekonomian masyarakat dan menggali sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG).
Salah satu skema yang dapat membangun ekonomi masyarakat dan menjadi sumber PAG adalah memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)—secara nasional disebut BUMDesa.
Wacana Penguatan BUMG ini sudah bergulir sejak beberapa tahun silam. Aceh merupakan Provinsi yang paling banyak memiliki BUMG. Nyaris semua gampong sudah memiliki BUMG.
Sebagai konsekwensi dari program pemerintah aceh periode 2007-2012, BUMG lahir bersamaan dengan digulirkannya program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Itulah sebab, Aceh paling banyak BUMG.
Dalam pelaksanaannya, tidak semua BUMG berjalan efektif, ada yang jalan ditempat, bahkan sudah tidak jalan lagi.
Berdasarkan pengamatan saya, tersendatnya pengelolan BUMG di pengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Sumberdaya manusia yang terbatas. Desa tidak memiliki banyak pilihan sumberdaya manusia.
Setelah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, kebanyakan pemuda desa mencari jalan hidup di kota. Untuk mengantisipasi masalah ini, gampong dapat melakukan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia.
Pada beberapa kasus, keterbatasan ini juga dapat terjadi karena aspek politis, misalnya pengurus atau masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda pilihan dengan Geuchik di saat Pilciksung.
Kedua, kekurangan ide. Sebagai badan usaha, tentu BUMG harus memiliki “core bisnis”, sektor apa, komoditi apa yang hendak diusahakan.
Kalau kita lihat jenis usaha yang dimiliki oleh BUMG, hampir delapan puluh persen menyewakan alat perlengkapan pernikahan, menyewakan hand traktor, dan Pinjam-pijam (karena sedikit sekali yang simpan).
Untuk mengatasi persoalan yang kedua ini, bisa dimulai dengan membentuk kepengurusan BUMG yang solid. Kemudian berkonsultasi dengan pihak ketiga yang dianggap mumpuni dibidang itu, baik dari pemerintah kabupaten seperti BAPPEDA, DPMG, Pendamping Desa atau akademisi dari Perguruan Tinggi atau pihak lain yang dianggap mumpuni.
Ketiga, Krisis kepercayaan masyarakat. Masalah ketiga ini sering muncul. Mungkin, pengalaman masa lalu yang kurang baik menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada BUMG.
Sebenarnya kesalahan itu belum tentu sepenuhnya ditujukan kepada BUMG. Persoalan itu sering terjadi pada saat simpan pinjam, mulai dari Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP), sampai pada Simpan-Pinjam PNPM.
Ditambah lagi ada beberapa BUMG yang pengurusnya tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Sebenarnya hal tersebut bisa diantisipasi jika segala sesuatu yang menyangkut BUMG dilakukan dengan transparan, mulai dari perekrutan pengurus, qanun yang mengatur mengenai bagi-hasil, berapa persen untuk pengurus, berapa persen untuk gampong.
Keempat, Manajemen yang kurang baik. Poin ini ada kaitan nya dengan sumberdaya manusia tadi. Lebih spesifik berkaitan dengan internal-kelembagaan BUMG.
Di sisi lain, di saat kita berharap banyak kepada pengurus atau manajemen BUMG, di situ pula mereka tidak boleh menerima anggaran yang bersumber dari APBG. Untuk BUMG yang belum memiliki penghasilan dari bagi hasil, barangkali agak terkendala dengan situasi ini.
Kelima, Kurangnya Modal. Point ini saya dapatkan di saat melakukan Focus Group Discussion dengan Geuchik. Namun permasalahan ini terbantahkan dengan hadirnya anggaran desa.
Sebagian aparatur gampong ketika tidak ada aturan yang mewajibkan penyertaan modal, ditambah lagi dengan kondisi BUMG yang jalan di tempat, mereka enggan untuk menganggarkan di APBG.
Keenam, Pemasaran. Beberapa BUMG, mereka sudah berhasil menemukan “core bisnis”, namun terkendala dalam hal pemasaran. Untuk kondisi seperti ini, saya kira pemerintah desa melalui BUMG dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta untuk membantu pemasaran.
Jika mengacu dari beberapa kendala tadi, masih ada harapan BUMG bisa menopang perekonomian gampong. Syarat mutlaknya: pemimpin harus memiliki visi untuk memajukan BUMG.
Minimal, isu BUMG ini masuk kedalam program strategis pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah gampong.
Pemerintah gampong jangan takut untuk membenahi internal-kelembagaan BUMG, memeperbaiki manajemen. Mulai dari kepengurusan, dasar hukum yang mengatur sekurang-kurangnya tentang kelembagaan, penyertaan modal, skema bagi hasil. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada manajemen, penyertaan modal, dan jangan lupa dikontrol dan dibina.
Jika ini terjadi, sebagian dari tujuan kehadiran dana desa ini sudah kita lakukan. Jika BUMG di daerah lain bisa kuat dengan kehadiran dana desa, kenapa di gampong kita tidak?
Di luar itu semua, inilah proses yang harus kita kerjakan. Semoga jadi amalan sosial yang akan kita pertanggungjawabkan, kelak!
Tulisan ini sudah pernah tayang di AY Corner