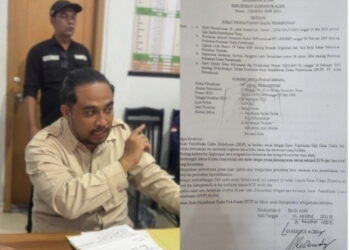Oleh: Alja Yusnadi
Saya sudah lama tidak mengisi situs web ini, sampai-sampai, saya diledek oleh Riza, Pimpinan Umum media Analisaaceh.com Riza lah yang membantu kehadiran web pribadi saya ini untuk menampung jika syahwat menulis saya meninggi, seperti di awal terjadinya Pandemi.
Namun, sudah dua bulan ini, selera menulis saya menurun drastis, sebenarnya bukan hanya karena selera, ada faktor-faktor lain, kalau dalam istilah ekonomi tidak cateris paribus. Beberapa kali ada dorongan untuk menulis, tapi masih kalah dengan faktor-faktor lain tadi itu.
Kali ini, saya memaksa diri untuk menulis, biar tidak lupa, dan agar bisa saya baca kembali untuk beberapa waktu ke depan, entah setahun, dua tahun, empat tahun yang akan datang, itupun kalau diberi umur panjang, yang jelas ini harus ditulis. Satu lagi, untuk mengendorkan urat-urat syaraf yang sudah terlanjur tegang akibat tugas yang menumpuk, apalagi setelah disemprot seorang pendekar kebijakan pembangunan pertanian beberapa hari yang lalu.
***
Dalam sebuah group whatsapp, yang anggotanya adalah pembelajar ilmu-ilmu ekonomi pertanian, calon-calon analisator kebijakan pertanian, calon-calon pembuat kebijakan pertanian, seorang teman, sebut saja namanya Qiki, beberapa kali menulis soal udut. Ya, udut. Saya jarang sekali mendengar istilah ini. Namun, saya mencoba memahami dengan cara mencocok-cocokkan artinya dengan rangkaian kata sebelum dan setelah kata udut. Dan saya hampir mendapatkan artinya, berkaitan dengan rokok.
Saya lupa, kenapa tidak cek saja ke kamus Bahasa. Awalnya, saya duga ini Bahasa Jawa. Rupanya udut sudah terdaftar di kamus Bahasa Indonesia, artinya: menghisap rokok, dan dugaan saya benar. Entah ini Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa daerah, entah Bahasa Indonesia dari sono nya, yang jelas saya sudah mendapatkan artinya.
Menariknya, teman saya itu memformulasikan manusia dengan mengudut. Katanya, manusia itu sejak kecil sampai dewasa tidak bisa lepas dari mengudut, tidak bisa tidak “terpaksa” menghisap, begitulah kira-kira.
Apa maksudnya? Prof. Qiki tidak melanjutkan pembahasannya. Sejauh ini, manusia itu sering disebut sebagai Homo Sapiens. Terakhir, saya membaca Homo Sapiens yang ditulis dengan sangat renyah oleh Yuval Noah Harari, sejarawan lulusan Oxford University berkebangsaan Israel.
Harari menggambarkan bagaimana evolusi makhluk yang dia sebut Sapiens. Mulai dari 70,000 tahun yang lalu hanyalah hewan tak penting yang sibuk sendiri di sudut Afrika. Bermilenium-milenium berikutnya, Sapiens berkembang menjadi penguasa planet dan menjadi terror bagi ekosistem.
Pada fase ini, Sapiens menjadi pusat peradaban, sekelilingnya boleh diekploitasi untuk kepentingan Sapiens. Fenomena alam yang terjadi dalam rentang waktu itu di capture oleh saintis, menurunkannya dalam berbagai bentuk ilmu: Biologi, Fisika, Metematika, Astronomi, Ekonomi, Psikologi dan seterusnya.
Hampir semua cara pandang itu merusak. Hal ini disampaikan oleh Fritjof Capra, terutama yang mekanistik, yang Sapiens-ansih, yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan.
Menurut Capra, sudah saatnya kita memandang alam ini secara equel. Dari sisi ekonomi misalnya, dia mengkritik cara pandang ekonom, baik yang Konvensional, Neoklasik, Marxis, Keynesian dan pasca Keynesian. Menurut Capra, para ekonom itu kurang memiliki perspektif ekologis, cendrung memisahkan ekonomi dari struktur ekologis yang melingkupinya dan cendrung menggambarkannya dalam pengertian model-model teoritis yang sederhana dan tidak realistik.
Untuk menggambarkan bagaimana ambisiusnya Sapiens itu sekarang, saya mengutip lagi apa yang disampaikan Harari. Menurut dia, Sapien nyaris menjadi tuhan, hampir menggapai bukan hanya kemudahan abadi, melainkan juga mencipta dan merusak.
Soal daya rusak ini tidak usah jauh-jauh, lihat saja bagaimana negara-negara maju penghasil terbesar emisi karbon melalui pabarik-pabrik yang outputnya untuk memenuhi keinginan Sapiens sedang disibukkan dengan isu deforestasi, global warming, climate change, dan seterusnya. Semua ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena ulah tangan sebagian sapiens, untuk mengisi perut sebagian sapiens pula.
Lalu, bagaimana gambaran ke depan? Akankah Sapiens ini akan berevolusi lagi? Setidaknya begini, dengan kecanggihan teknologi yang perkembangannya begitu cepat bahkan melampaui kebijaksanaan yang dihasilkan manusia membuat kita bisa—setidaknya membayangkan- bagaimana manusia di masa yang akan datang.
Bisa jadi, salah satu yang berevolusi adalah kapasitas otak. Seperti cerita jerapah, otak yang kapasitas kecil tidak akan mampu bertahan di tengah gempuran teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Kemudian menjadi dataisme, semua berbasis data.
Di Jepang, untuk menghadapi situasi ini, pemerintahnya menyiapkan Society 5.0, untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Saya melihat, Society 5.0 ini adalah bagian dari upaya manusia untuk menyeimbangkan dengan kemajuan teknologi.
Semuanya tidak boleh menang sendiri, harus berjalan beriringan. Inilah tugas berat manusia, termasuk soal keilahian. Untuk menggambarkan situasi evolusi manusia di masa yang akan datang itu, Harari menyebutnya Homo Deus, Mary Belknap menyebutnya Homo Deva, ada juga yang menyebut Homo Data. Yang lebih penting lagi mencari gelombang ketuhanan, yang jika berpegang pada ujung gelombang itu akan menghantar kita pada pangkalnya.
Lalu, bagaimana dengan Homo Udut? Jika mengudut itu seperti arti dalam kamus, dikembalikan kepada cara pandang masing-masing. Anda yang beranggapan dengan mengudut ikut serta membangun bangsa melalui pajak, silakan. Bagi Anda yang mengatakan mengudut dapat merobek kantong dan kesehatan, juga silakan. Kalau saya pengudut berat, tapi itu dulu, saya sudah berhenti sejak 3 tahun yang lalu.
Atau, untuk menyandingkan dengan Homo Deus, Homo Deva, kita gunakanlah Homo Udut ini untuk menggambarkan manusia yang di dalam dirinya sudah ada cahaya. Cahaya di atas cahaya, yang suci lagi menyucikan…[Alja Yusnadi]