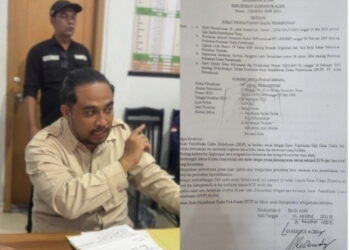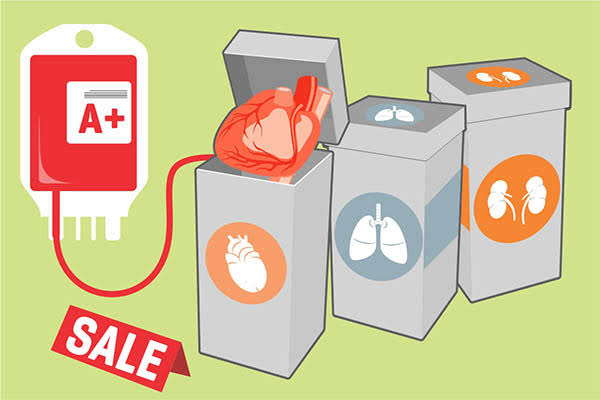Oleh: Alja Yusnadi
Anda akan mengetahui makna damai itu jika pernah merasakan bagaimana susahnya hidup di saat konflik. Saya tidak tahu bagi pelaku, apakah mereka menikmati atau juga sama tertekan seperti saya.
Lagi panas-panasnya konflik, saya berada pada usia anak-anak sampai remaja. Ada beberapa peristiwa penting yang sampai hari ini masih terekam di memory saya yang terbatas.
Diantaranya adalah peristiwa Sabtu berdarah. Entah komando siapa, masyarakat disuruh ikut demo ke halaman Polres Aceh Selatan di Tapaktuan. Anak muda, orang tua berbondong-bondong. Ada yang bawa kendaraan sendiri, ada juga yang menumpang kendaraan umum.
Kabarnya, ada “orang kita” yang ditahan di Polres itu. Memang, pada saat itu Aceh baru saja memulai konflik. Belum ada pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO), masyarakat berada dipuncak uforia. Mereka terpacu adrenalinnya.
Saya tidak hadir dalam peristiwa itu, karena masih anak-anak. Kalau tidak salah, masih kelas VI SD. Tidak lama berselang aparat menembak pengunjuk rasa, entah ke atas, entah ke bawah.
Jelasnya ada korban. Saya tidak ingat berapa angka pastinya. Beberapa orang yang saya kenal ikut menjadi korban, tidak meninggal, hanya cacat fisik, seumur hidup.
Dua diantaranya sekampung dengan saya: Suhardi dan Cut Mawar. Suhardi kena tembakan di tangan. Cut Mawar kena tembakan di kaki. Keduanya meninggalkan bekas, sampai saat ini.
Berikutnya, mengungsi. Kali ini saya ikut. Tempatnya di pekarangan SMK N 1 Pasieraja. Dulunya politeknik pertanian. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah, semua harus mengungsi. Begitu intruksinya.
Saya tidak tahu persis, siapa yang memberi instruksi itu. yang jelas, tua-muda, anak-anak, balita, lansia, semua dipaksa mengungsi. Kecuali beberapa orang yang mendapat izin untuk menjaga gampong. Begitu katanya.
Malam itu kami berbondong-bondong ke tenda pengungsian. Berjalan kaki sejauh 7 sampai 10 km, membawa bekal ala kadarnya. Pada saat itu belum ada kejadian luar biasa yang memaksa harus mengungsi. Tapi itu tadi, perintah harus dijalankan.
Bagi anak-anak senang bukan kepalang, melompat sepanjang jalan. Sampai akhirnya beberapa hari di dalam tenda, kejumudan melanda.
Saya dan keluarga menempati tenda dibagian depan SMK. Situasi sekolah berubah seketika. Tidak ada aktivitas belajar-mengajar. Fasilitas banyak yang rusak. Perlengkapan banyak yang hilang.
Entah berapa lama kami di situ, saya tidak begitu ingat. Aktivitas tidur, makan saja. sampai akhirnya stok pangan menipis. Orang dewasa saya perhatikan ada yang piket, menjaga pintu masuk depan SMK.
Ada juga yang merazia kendaraan lewat, mereka mencari orang luar Aceh. Semacam ada anggapan, selama ini orang-orang itu menjajah Aceh. padahal tidak. Bukan mereka.
Kalau maksudnya Pemerintah, bisa jadi. Menindas melalui kebijakan yang tidak adil. Tidak merata. Terjadi ketimpangan pembangunan. Pemerintah mengeruk hasil alam saja, tanpa memperhatikan pembangunan daerah.
Situasi itu tidak berlangsung lama. Beberapa truck reo membawa serdadu, saya tidak ingat dari kesatuan mana. Mereka menyuruh kami pulang. Sejak saat itu, situasi sudah mulai mencekam. Kami mengemasi barang-barang di bawah todongan senapan.
Babak baru dimulai. Sejak saat itu, bermacam kesatuan serdadu non-organik silih berganti mendirikan pos, di gampong-gampong.
Mereka yang sebelumnya menyulut perlawanan tidak kelihatan batang hidungnya. Masyarakatlah yang jadi samsak. Sejak saat itu kehidupan tidak menentu. Serdadu pegang kendali.
Kejadian berikutnya, kalau saya tidak salah sekira tahun 2001. Malam. Bulan puasa. Dor, dor, dor. Terdengar suara tembakan. Entah berapa kali jumlahnya.
Saat itu saya sudah Sekolah Menengah Pertama. Esoknya terdengar kabar, 3 saudara saya di pasi—dekat laut– meninggal ditembak. Pelakunya tidak jelas dari kesatuan mana.
Satu diantara yang meninggal itu saya panggil cutbit Mizan. Cutbit itu panggilan untuk adik Ayah atau Ibu. Mizan itu namanya. Cutbit Mizan adalah adik sepupu Ibu saya.
Dua orang lagi adalah abang ipar atau suami dari kakak Cutbit Mizan. Mereka dituduh GAM. “Brengsek, tuduhan yang tidak berdasar,” gumam saya waktu itu. Mereka merampas 3 nyawa malam itu.
Ketiganya dikembumikan satu liang, di pemakaman keluarga. Saya ikut mengantar sampai kuburan.
Ini bukan hanya soal kematian. Tapi jauh dari itu, lebih sepuluh orang anak yatim yang ditinggalkan.
Bisa Anda bayangkan, bagaimana sengsaranya kehidupan keluarga itu.
Sekarang, anak-anak yatim itu ada yang sudah besar. Sudah menikah. Pun demikian, pembunuh orangtua mereka masih misteri, belum terungkap.
Ini tentu hanya contoh, yang dekat dengan saya. Berapa banyak yang nasib serupa atau yang lebih sadis dari itu? Itulah gunanya kesepahaman antara GAM dengan Pemerintah. Gunanya MoU Helsinki itu. Gunanya Undang-undang Pemerintahan Aceh itu. Gunanya BRA itu.
Damai itu menghentikan pertikaian dan memenuhi hak korban. Apakah hak-hak korban itu sudah dipenuhi? Jangan sampai, kasus-kasus seperti itu menjadi residu perdamaian.
Residu, cepat ditangani akan hilang, bersih. Jika dibiarkan, lama-lama menjadi banyak, menyumbat, dan akan menimbulkan benih-benih baru.
Selamat memperingati hari penandatanganan MoU Helsinki yang sekaligus menjadi Hari Perdamaian Aceh. Lima belas tahun sudah…[]