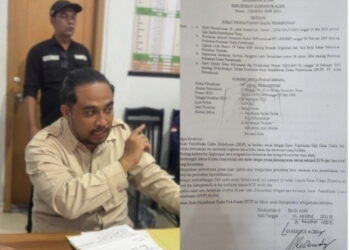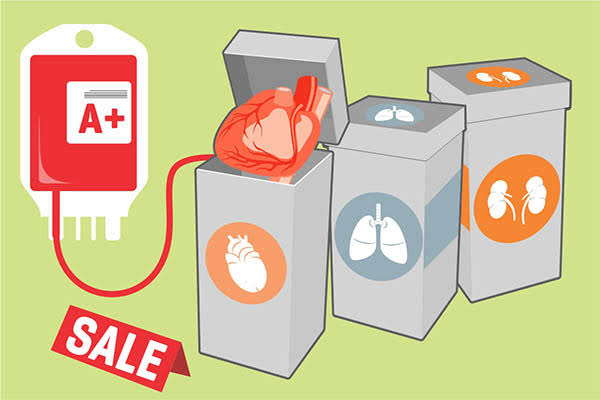Oleh: Alja Yusnadi
Nova Iriansyah sudah lebih dua tahun menjabat sebagai Plt. Gubernur Aceh. Pasca ditangkapnya Irwandi Yusuf—Gubernur hasil pilkada 2017—oleh KPK Juli 2018 lalu.
Irwandi hanya sempat memimpin selama 1 tahun. Banyak janji kampanye yang belum sempat dilaksanakannya.
KPK mencokok Irwandi atas kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Ahmadi, Bupati Bener Meriah –juga sudah divonis bersalah—melalui orang dekat Irwandi—juga sudah divonis—menyuap Irwandi.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat—Tipikor—telah memvonis Irwandi dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta.
Tidak terima, Irwandi melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Hukuman Irwandi diperberat menjadi 8 tahun penjara.
Terakhir, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta.
MA telah mengeluarkan putusan pada pertengahan Februari 2020. Ingkrah—sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sudah delapan bulan keputusan itu keluar, namun Gubernur Aceh masih pelaksana tugas.
Usut-punya usut, rupanya Presiden sudah mengeluarkan Kepres tentang pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh sejak Juli 2020. Artinya, sudah tiga bulan yang lalu.
Seyogyanya, setelah keluar SK itu, DPRA menggelar sidang paripurna untuk memberhentikan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh dan mengusulkan Nova Iriansyah sebagai Gubernur defenitif.
Namun, itu belum terjadi. Memang, DPR Aceh sejak dilantik sampai sekarang sedang sibuk mengurus urusan internal. Belum beres-beres. Mulai dari konflik Alat Kelengkapan Dewan, hingga interpelasi Kepala Pemerintah Aceh.
Semua itu, akibat buntunya komunikasi DPRA dengan Pemerintah Aceh.
Mungkin, karena itu juga, DPRA “lupa” membahas nasib Gubernur Aceh, walaupun hanya mekanisme formal saja. Soalnya, DPRA tidak punya hak dan wewenang untuk tidak mengusulkan Nova yang merupakan Wakilnya Irwandi Yusuf.
Safaruddin, Wakil Ketua DPRA mengatakan, surat presiden itu sudah kedaluwarsa, tidak mungkin lagi untuk dibahas oleh DPRA. Karena, menurut politisi Partai Gerindra itu, Undang-undang memberikan waktu paling lama 10 hari. Lha, ini sudah 3 bulan, hampir 90 hari. Surplus 80 hari.
Ups, maksud Safaruddin, dia menerima surat itu 13 Agustus, dan telah diserahkan kepada Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin. Sementara surat diteken 17 Juli. Masih lebih 10 hari.
Atas dasar itulah, pimpinan DPRA—lebih khususnya Ketua dan Wakil Ketua III—tidak meneruskan ke rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ke sidang paripurna.
Bukankah pimpinan DPRA itu kolektif-kolegial? Harusnya begitu. Namun, dalam kenyataannya tidak. Sebagaimana disampaikan Dalimi, Wakil Ketua I. Dia sudah lama melihat surat itu di meja Wakil Ketua III.
Dalimi mengaku tidak pernah diajak rapat oleh Ketua mengenai surat itu.
Ketua dan Wakil ketua III merupakan bagian dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Kalau dalam istilah politik Malaysia, KAB itu pembangkang, walau tidak begitu tepat untuk sistem politik Indonesia yang menganut sistem Presidensial.
Sementara Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II di luar KAB. Apalagi Dalimi, dia merupakan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh yang Ketuanya adalah Nova Iriansyah yang sedang dipolemikkan itu.
Apa yang sedang terjadi? Pertama, DPRA melalui Ketua dan Wakil Ketua III memang sengaja tidak membahas surat itu. Mau tidak mau, publik menilai ada kaitannya dengan hubungan yang renggang antara DPRA dengan Pemerintah Aceh.
Bukan apa-apa, sungguh di luar akal surat Presiden tidak sampai ke DPRA dalam tempo kurang dari 10 hari. Soalnya ini zaman teknologi, bukan zaman batu.
Bisa juga, membiarkan lewat 10 hari, lalu dikeluarkan Kepres pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur sisa masa jabatan oleh Presiden. Tanpa melalui proses pengusulan DPRA.
Kedua, Surat Presiden terlambat sampai ke DPRA. Walau “hanya” administrasi, ini urusan serius. Perlu audit forensik. Dimana mengendapnya.
Bagaimana nasib Gubernur defenitif? Sebenarnya tidak kendala. Hanya saja, secara legitimasi politik agak berkurang, karena tidak diusulkan DPRA. Tapi, toh selama ini legitimasi politik di DPRA memang sudah lemah.
Bisa juga, DPRA berdalih pelantikan Gubernur Aceh cacat prosedur, karena tidak melalui pengusulan DPRA, dan itu melanggar kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Ujung-ujungnya, sampai habis habis masa jabatan Nova—Juli 2022—hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh selamanya dalam kegaduhan.
Bagi Nova, baik Plt maupun defenitif tidak begitu berarti. Toh, dia sudah menjadi Plt selama dua tahun tanpa kekurangan satu kekuatan politik apapun.
Nova berhasil menjalankan kebijakan yang harus mendapat persetujuan DPRA. Bahkan, dengan status Plt-nya itu, Nova berhasil “menjinakkan” DPRA untuk mensahkan APBA 2020 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tercepat dalam sejarahnya.
Lantas, siapa yang dirugikan dalam konfigurasi politik yang diagonal ini, Nova? DPRA? Rakyat Aceh?
Kalau rakyat Aceh sepertinya tidak. Mau Plt, Pj, defenitif, bahkan tanpa Gubernur sekalipun tidak berpengaruh signifikan, kecuali Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) itu. langsung berdampak. Selebihnya, biarlah itu menjadi perkara elit politik saja…[Alja Yusnadi]