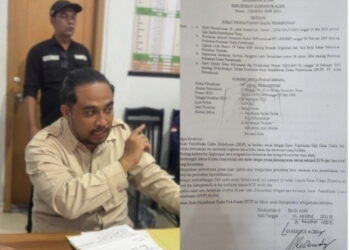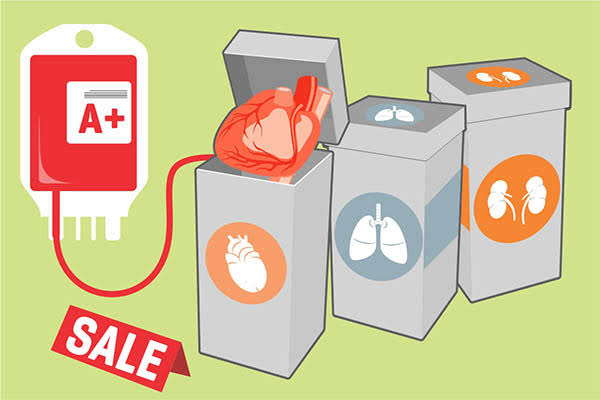Oleh: Alja Yusnadi
Era digital telah menjungkir-balikkan banyak hal. Baru-baru ini, jagad maya dibuat heboh oleh postingan akun twitter BEM UI, mereka mengkritik Presiden Jokowi. Mereka menyebutnya The King of Lip Service disertai dengan meme.
Kritik itu direspon banyak pihak. Mulai politisi, akademisi, hingga pengurus MUI. Tanggapan lebih banyak yang mendukung, terutama dalam koridor kebebasan berekspresi.
Sebenarnya, yang membuat heboh itu bukan kritik dari BEM UI, karena, sebelumnya kritik serupa juga sudah ada, termasuk oleh mahasiswa UGM yang juga almamaternya Jokowi. Yang membuat ramai itu justru respon dari pihak rektorat UI.
Rektorat memanggil Ketua BEM dan beberapa pengurus, meminta klarifikasi. Celakanya, surat itu bocor ke media sosial. Sejak itulah, rektorat UI menjadi samsak, dihujat oleh banyak pihak, termasuk oleh kalangan sendiri.
Dari beberapa hujatan itu, yang menarik perhatian saya yang mengaitkan pemanggilan mahasiswa itu dengan posisi Rektor UI sebagai salah satu Komisaris di BUMN.
Lebih luas lagi, mengaitkan antara akademisi dengan kekuasaan. Bagaimanakah hubungan yang seharusnya antara akademisi dengan kekuasaan, dengan pemerintah? Apakah kampus—akademisi di dalamnya—harus menjaga jarak dengan pemerintah? Atau Kampus menjadi bagian dari pemerintah? Atau berjalan berdampingan?
Secara legal-formal, kita bisa melihat statuta kampus dan aturan tentang ASN atau tentang Dosen. Apakah Dosen, Rektor dibenarkan memegang jabatan di pemerintah, baik sebagai Komisaris, Menteri, Penasehat, Staf Ahli, dan sebagainya? Tegak lurus saja dengan aturan, jika melanggar silakan disangsi.
Fakta ini sudah ada sejak lama, sampai sekarang. Ada sederet nama akademisi yang membantu kerja-kerja pemerintah, baik langsung maupun dalam bentuk program, bahkan ada yang menjadi Menteri. Di Aceh, beberapa Gubernurnya pernah menjadi dosen, termasuk yang lagi menjabat.
Dalam waktu yang sama, tidak sedikit pula akademisi yang memilih jalan berbeda. Membantu pemerintah dari luar, dengan cara mengkritik. Mereka-mereka inilah yang berupaya menjaga nalar publik, yang memberikan masukan melalui tulisan-tulisan populer di media masa, postingan-postigan di media sosial.
Ada juga, akademisi yang tidak masuk ke pemerintahan, tidak pula mengkritik, hanya sibuk dengan urusan kekampusannya saja, itupun kalau iya.
Apakah akademisi yang ideal itu model yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kampus, hampir sama dengan institusi lain, selalu ada dua kutub, pun yang di tengah-tengah itu. Selanjutnya, ini soal selera. Ibarat makanan, ada yang suka pedas, ada yang suka manis, dan seterusnya.
Semestinya, negara ini diurus oleh orang-orang ahli. Kalau memungkinkan, negara ini diurus oleh orang-orang seperti yang dikampus itu. Namun, kita telah memilih jalan pembagian kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.
Jika ada orang kampus yang hendak menjadi eksekutif atau legislatif, mesti menanggalkan status pegawainya, lalu bertarung menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Yudikatif merupakan jenjang karir, jadi tertutup jalan bagi akademikus, kecuali untuk beberapa lembaga seperti KPK.
Yang paling mungkin itu, orang-orang kampus membantu ketiga cabang kekuasaan itu dari dalam, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Di eksekutif, tenaga kampus dapat membantu pemerintah dengan menjadi tenaga Ahli, Staf Ahli, Penasehat, bahkan Mentri.
Legislatif juga membutuhkan Tenaga Ahli untuk menjalankan peran dan fungsinya. Bayangkan saja, para wakil rakyat ini berasal dari berbagai kalangan, sesuai rakyat yang diwakilinya.
Katakanlah, kekuasaan itu penuh onak dan duri, penuh tipu muslihat. Lalu, apakah akademisi hanya melihat dari jarak jauh, tanpa tergerak untuk memperbaikinya? Saya kira, ini juga pilihan yang kurang baik. Bukan apa-apa, kampus pun merupakan produk politik, tunduk di bawah peraturan yang dibuat oleh kekuasaan tadi.
Hemat saya, kekuasaan harus selalu menjaga keintiman dengan kampus, sampai klimaks. Tujuannya bukan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk membungkam suara-suara kritis di kampus, melainkan, di kampus tersimpan mutiara hikmah. Kenapa? Karena di situlah tempat berkumpulnya orang-orang yang mencitai ilmu pengetahuan.
Ketika pemerintah memberikan tugas kepada orang-orang terdidik itu untuk mengurus BUMN, menjadi penaset Mentri, bahkan menjadi Mentri, itu artinya karena ilmunya. Bukan untuk mengontrol orang-orang kritis di dalamnya.
Yang paling penting, di manapun berada, para cerdik pandai itu harus mampu menjadi penanda, pembeda, harus mampu menjaga etik. Mengenai Rektor Komisaris itu? Ahhhh, bukan urusan saya…[Alja Yusnadi]